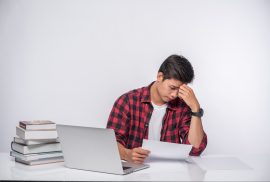Stres merupakan salah satu tantangan kesehatan mental yang paling umum dialami oleh mahasiswa. Beban akademik yang tinggi, tekanan untuk berprestasi, tuntutan organisasi, serta ketidakpastian mengenai masa depan seringkali menjadi sumber stres yang berkelanjutan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, mahasiswa mengembangkan berbagai strategi koping untuk mengelola stres. Selain olahraga, tidur, dan dukungan sosial, konsumsi makanan tertentu juga kerap dianggap dapat membantu meredakan stres. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi cokelat. Anggapan bahwa cokelat dapat mengurangi stres sudah sangat populer di kalangan mahasiswa. Namun, penting untuk mengkaji apakah klaim tersebut memiliki dasar ilmiah atau sekadar mitos yang berkembang secara sosial.
SDG 3
Menonton film bagi kebanyakan orang menjadi cara sederhana untuk melepas lelah setelah rutinitas padat atau sekedar mengikuti cerita yang tengah populer. Namun tahukah Anda, jika aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tetapi dapat membantu dalam proses healing atau penyembuhan emosional dan psikologis.
Menonton film untuk menjaga kesehatan menat ini dikenal dengan istilah cinematherapy. Lewat film menjadi wahana untuk menumbuhkan kesadaran diri, empati, dan pemaknaan terhadap pengalaman hidup.
Libur telah tiba, libur telah tiba! Akhirnya, penantian akan liburan akhir semester sudah terwujud. Sebelum waktu lenggang ini, kamu sudah berencana melakukan segala hal produktif, mulai dari belajar hard skills dan soft skills baru sampai terpikir cicil materi semester depan. Wah, banyak sekali deh kegiatan positif yang ingin dilakukan!
Akan tetapi, semuanya hanya wacana belaka. Scrolling di sosial media lebih menarik dibandingkan eksekusi perencanaan yang telah dibuat. Waktu terasa panjang, pasti bisa melakukan semua wishlist tadi. Penundaan terus terjadi hingga semester depan datang. Perasaan menyesal mulai tumbuh setelah masa liburan selesai.
“Kenapa kemarin aku nggak lakuin ini ya,”
“Coba aja kemarin aku nggak terlena sama yang lain, pasti sekarang aku udah punya skill itu,”
Dan, masih banyak variasi kalimat penyesalan lainnya. Lelah dalam penyesalan? Pasti. Rasanya ingin mengulang waktu kembali, walaupun belum tentu jika diulang kita akan melakukan hal yang positif.
Penguasaan keterampilan teknis bukan menjadi satu-satunya modal untuk sukses di dunia profesional. Entrepreneur dan content creator Raymond Chin menegaskan bahwa penguasaan soft skills seperti komunikasi dan empati menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan seseorang dalam berbisnis. Menurutnya, keduanya adalah kemampuan yang tidak dapat digantikan teknologi, sekaligus penentu apakah seseorang mampu membangun relasi, memimpin, dan bertahan di industri yang terus berubah.
“Memahami orang lain dan tahu caranya menjadi pemimpin, dengan dua skill itu kita tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi,” tegasnya.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) memberikan berbagai bentuk dukungan bagi mahasiswanya yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini diambil untuk memastikan mahasiswa tetap dapat menjalani kegiatan akademik dengan lancar meski berada dalam situasi sulit yang menimpa keluarga mereka. Saat ini tercatat 18 mahasiswa FEB UGM dari berbagai program studi sarjana dan pascasarjana yang terdampak bencana.







Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM berhasil menyumbangkan tiga medali perunggu dari Pekan Olahraga dan Seni Universitas Gadjah Mada (PORSENIGAMA) 2025 cabang tenis lapangan.
Medali perunggu pertama tersebut diraih oleh Ina Winata Kusuma Hasibuan (Ilmu Ekonomi, 2022) dari kategori tunggal putri. Medali perunggu kedua diraih oleh Ina Winata Kusuma Hasibuan (Ilmu Ekonomi 2022) dan Aurelia Yuma Citra Dwinda (Ilmu Ekonomi, 2022) dari kategori ganda putri. Medali perunggu ketiga diraih oleh Muhammad Rafsya Sefyuan Al Fathan (Akuntansi, 2023) dan Iasmina Ligia Radu (Economics-Exchange Program, 2025) dari kategori ganda campuran.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyediakan fasilitas sarapan gratis dan layanan pendukung lain untuk memastikan mahasiswa dapat menjalani Ujian Akhir Semester (UAS) dengan optimal. Program ini berlangsung selama periode UAS, yaitu 8–19 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh mahasiswa program sarjana FEB UGM.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UGM, Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D., menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk komitmen fakultas dalam mendukung mahasiswa selama ujian.
Kesibukan kuliah, organisasi, dan tuntutan pribadi sering membuat mahasiswa lupa satu hal yaitu mendengarkan diri sendiri. Memahami diri melalui proses refleksi dengan kesadaran penuh atau mindfulness dapat dilakukan melalui teknik STOP.
Psikolog, Dwi Nurul Baroroh, M.Psi., memaparkan teknik STOP terdiri dari empat langkah untuk mengelola emosi. Pertama, Stop atau berhenti sejenak dari segala aktivitas rutin. Lalu, Take a deep breath atau mengambil napas dalam melalui hidung dan hembuskan perlahan melalui mulut hingga beberapa kali sampai merasa lebih tenang. Berikutnya, Observe atau mengamati apa yang dirasakan oleh tubuh, pikiran, dan perasaan. Terakhir, Proceed atau melanjutkan aktivitas setelah merasa lebih tenang dan fokus.
Berawal dari kesulitan yang dihadapi mahasiswa rantau dan tinggal di kos-kosan yang sering kesulitan mencari bantuan layanan rumah tangga seperti perbaikan hingga membersihkan kamar kos, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) mengembangkan gagasan platform digital Bantoo. Platform digital yang diusung menghubungkan antara pengguna dengan penyedia jasa layanan.
“Ketika mengalami kerusakan atau masalah kecil di kamar, kebutuhan perbaikan masalah kos seringkali bergantung terhadap penjaga dan kenalan pemilik kos terbatas pada ketersediaan dan kemampuan teknis. Selain itu, mencari jasa informal memiliki risiko harga yang tidak transparan atau terlalu tinggi, terlebih lagi untuk anak rantau,” ungkap Tabina Maritza Wisnu selaku CEO Bantoo.
Sudah beberapa bulan dunia kampus telah dilewati oleh mahasiswa baru FEB UGM. Banyak tawa, kecewa, khawatir pada indeks nilai, takut menghadapi dosen dan mata kuliah, dan beberapa hal lainnya yang sudah dialami selama paruh waktu menjadi mahasiswa baru. Transisi dari dunia sekolah menengah ke universitas, dari siswa menjadi mahasiswa, mungkin terasa berbeda bagi setiap orang. Ada yang merasa transisi ini mudah, ada yang bilang lumayan berat, dan bahkan beberapa yang merasa sangat berat. Ini merupakan hal yang lumrah bagi mahasiswa sebagai individu dalam menghadapi fase kehidupan yang baru.